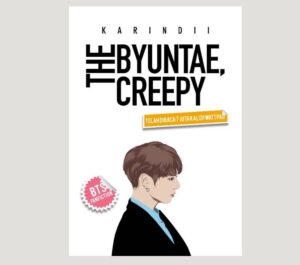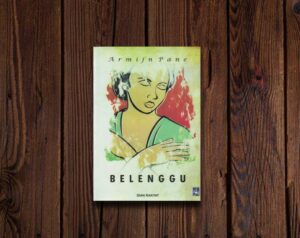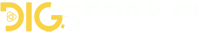Sebuah novel yang berjudul “Lelaki di Tengah Hujan”, karangan Wenri Wahar, beberapa waktu yang lalu dikirim ke alamat saya, oleh grup whatsapp alumni. Novel setebal 364 halaman ini diterbitkan oleh Penerbit Milestone ini, berkisah tentang seorang tokoh yang bernama “Bujang Parewa”.
Sekilas dari nama tersebut, saya pikir tokohnya orang Minang, karena kata “Parewa” itu, adalah salah satu kata bahasa Minang, yang berarti kurang lebih “Preman”. Ternyata setelah saya baca lebih detil, tokohnya berasal dari salah satu desa di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini mungkin membuat cerita terkesan “wagu”, meminjam kata bahasa Jawa untuk segala sesuatu yang dianggap tidak pantas/pas.
Dari isi cerita, kurang lebih isinya berkisah tentang bagaimana kisah tokoh utama (Bujang Parewa) yang digambarkan dengan penuh heroisme dan gerakan mahasiswa liberal tahun 80-an dan 90-an, yang dalam sejarahnya sempat membentuk sebuah partai yang kelihatan kiri dan sosialis, yaitu PRD (Partai Rakyat Demokratik).
Fokusnya tetap pada si tokoh utama, sehingga kurang lebih novel ini boleh dikata sebagai biografi si tokoh utama dalam kemasan novel fiktif yang diklaim sebagai novel sejarah. Mengapa saya bilang fiktif? Karena dalam cerita, lebih ditonjolkan kepahlawanan si tokoh utama, dengan berbagai hal yang tak penting, seperti kegemarannya akan rokok dan kopi panas, rambut gondrong yang suka dikibas-kibaskannya di tengah hujan. Selain itu, ada beberapa peristiwa sejarah yang dideskripsikan tidak sesuai persis dengan kenyataan yang terjadi. Contohnya seperti perpecahan FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta), dalam novel hanya diceritakan bahwa perpecahan terjadi karena perbedaan strategi taktik perjuangan yang diambil, menutupi realitas sebenarnya, yang mungkin kalau diceritakan bisa mencoreng-moreng kepahlawanan si tokoh utama dan organisasinya, yaitu PRD.
Untungnya sebelum bukunya saya lempar ke tong sampah, muncul seorang tokoh lain yang sangat menarik, yaitu Joni Trotoar. Saya sebenarnya tahu siapa nama asli kedua tokoh ini, yaitu si Bujang Parewa dan Joni Trotoar. Kebetulan saya pernah bertemu si Bujang Parewa ini dulu waktu saya masih mahasiswa, dan boleh dikata bukanlah sebuah pengalaman yang indah untuk dikenang. Saya juga pernah menjadi pendengar dari curahan hati beberapa kawan, yang dipecat dari PRD karena berseberangan secara politik dengan si Bujang Parewa ini, yang sekarang menjadi salah satu pejabat teras PRD.
Untuk Joni Trotoar, yang sudah almarhum, saya hanya mengenal dia dari puisinya yang dimuat di salah satu tabloid Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar. Lebih menarik sebenarnya membaca novel ini ketika tokoh Joni Trotoar muncul. Yang bersangkutan memang seorang legenda dalam gerakan mahasiswa tahun 90-an, yang tetap hidup dan berlawan bersama rakyat sampai akhir hayatnya. Dari puisi Joni Trotoar, yang berjudul “Benar”, yang ditampilkan cukup lengkap di halaman 229, sudah jelas sekali, siapa sebenarnya nama asli karakter “Joni Trotoar” ini dalam kehidupan nyata. Beda nasib mungkin dengan si Bujang Parewa (BP) yang ditugaskan di ibukota, Jakarta, sehingga memperoleh akses ekonomi politik yang lebih besar dibanding Joni Trotoar. Si BP ini juga pernah tercatat sebagai salah seorang pengurus pusat Partai Gerindra. Hal yang membuat ia sempat dikritik rekan-rekannya mantan PRD, karena Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sering dikaitkan dengan kasus penculikan aktivis-aktivis PRD di akhir kekuasaan Rezim Orde Baru.
Hal yang tak digambarkan dalam novel ini, adalah berbagai intrik yang ditimpakan pada Joni Trotoar, sebelum kepulangannya ke Kalimantan, untuk berobat. Entah mengapa, yang jelas kalau benar-benar konsisten dengan klaim sebagai novel sejarah, seharusnya semua fakta sejarah yang ada diungkap, supaya karakter yang digambarkan dalam novel, bukan hanya putih atau hitam sepenuhnya, karena dalam kehidupan semua manusia itu pada dasarnya memiliki sisi abu-abu.
Hal lain yang juga cukup menarik perhatian saya, adalah penggambaran tentang penyair kerakyatan, yang sampai sekarang masih hilang, Ketua Jaker (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat), yang juga anggota PRD, yaitu Widji Thukul, pada bab “Pria dengan Senjata Kata-Kata”. Lumayan, sepenggal kisah hidup Thukul, dan beberapa puisi perlawanannya diulas dalam bab itu.
Penggambaran tokoh dengan kacamata heroisme, dalam novel ini, kurang lebih mirip dengan gaya Budiman Sudjatmiko memuji-muji dirinya sendiri dalam buku “Anak-Anak Revolusi”. Hanya saja bedanya, kalau dalam buku megalomania “Anak-Anak Revolusi” (AAR) tersebut, karakter-karakter lain, yang juga ikut berjuang menentang Orde Baru bersama Budiman Sudjatmiko, tak begitu digambarkan. Sementara, dalam novel “Lelaki di Tengah Hujan” ini, sebagian besar tokoh-tokoh tersebut disebutkan, hingga yang jadi pahlawan bukan hanya BP seorang. Hanya satu yang jadi pertanyaan saya tentang ini, mengapa salah seorang sesepuh gerakan kiri, anggota PRD dan Jaker, yang juga alumni Filsafat UGM, Sahanudin Hamzah alias Hamcrut tidak digambarkan dalam novel ini? Apakah pengamatan saya yang kurang teliti, sehingga nama Hamcrut luput dari pandangan saya? Atau mungkin sudah digambarkan, tetapi dengan nama samaran? Entahlah. Yang jelas, sebuah novel sejarah tentang PRD, SMID, Filsafat UGM, Jaker, tak layak disebut sebagai novel sejarah, tanpa penggambaran tentang tokoh penting tersebut.
Hal-hal lain dalam novel ini yang tak digambarkan dalam buku AAR-nya Budiman Sedjatmiko, adalah budaya liberal yang diamalkan oleh para aktivis PRD dan gerakan mahasiswa liberal, yang mengaku kiri tahun 90-an, seperti budaya seks bebas, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Beberapa halaman dan bab novel ini cukup dihiasi oleh gambaran tentang hal tersebut. Selain itu, novel ini dibuka dengan peristiwa bom Tanah Tinggi, yang terjadi di akhir kekuasaan Soeharto. Hal yang tak diakui oleh Budiman, sebagai sebuah aksi dari PRD.
Akhir kata, novel “Lelaki di Tengah Hujan” ini sebenarnya cukup menarik untuk dibaca sampai akhir. Berbagai informasi terkait gerakan mahasiswa liberal, yang mengaku kiri, tahun 90-an, khususnya yang kemudian membentuk SMID dan PRD, tersaji lumayan banyak, walaupun sangat kurang lengkap. Berbagai fakta sejarah penting, tak digambarkan dengan jujur, sehingga bagi saya novel ini hanyalah sebuah fiksi belaka. Memang ada beberapa kutipan berita suratkabar, dan tanggal-tanggal tertentu, akan tetapi, tanpa penggambaran sebuah peristiwa sejarah secara lengkap dan terus terang, hanya akan menjadi sebuah dongeng indah untuk pengantar tidur belaka. Sebuah novel sejarah, dan novel gerakan kerakyatan yang baik, pada dasarnya bukanlah hanya sekedar sebuah penggambaran tokoh belaka, melainkan adalah penggambaran bagaimana kondisi sosial dan konflik yang melatari setiap peristiwa sejarah. Dan yang paling penting, adalah sebuah kejujuran dalam menggambarkan kebenaran.